Setelah setahun lumpur panas menyembur di bumi Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kehancuran semakin tak terperikan. Rumah, fasilitas sosial, pabrik, kantor dan sawah ladang terus-menerus berada dalam hitungan mundur menjadi tumbal pengorbanan, tenggelam ke dalam kubangan lumpur panas. Menatap alam di sekitar semburan lumpur panas, kita lalu seperti melihat sebuah the lost city, kota yang hilang. Ribuan penduduk beserta keluarga mereka merana dan dilanda depresi sosial (editorial Koran Tempo, 28 Mei 2007) lantaran kehilangan tempat berteduh, mata pencaharian serta kehilangan sukma kebudayaan di atas pelataran bumi tempat berpijak. Karena itu, musnah sudah apa yang disebut “alam terkembang menjadi guru”. Aspek statistikal yang dengan serta merta dapat dibaca sebagai potret kehancuran adalah magnitude investasi dalam ranah perekonomian masyarakat. Sekadar catatan, jumlah investasi di Sidoarjo dengan nilai Rp 5 juta hingga Rp 200 juta pada periode Januari-April 2007 hanya mencakup 8 industri. Bandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, terdapat 11 industri. Adapun industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 200 juta selama Januari-April 2007 tercatat 10 industri. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 14 industri. Secara keseluruhan data tersebut memperlihatkan fakta, bahwa sepanjang tahun 2006 ada 8 industri penanaman modal asing (PMA) dan 13 industri penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menanamkan investasi di Sidoarjo. Namun kontras dengan itu, selama Januari-April 2007 belum ada PMA dan PMDN yang mau menanamkan modal di Sidoarjo (Kompas, 28 Mei 2007, hlm. 15). Realisme ini dapat dibaca secara terang benderang dalam kaitan makna dengan bencana lumpur panas Lapindo yang meluluhlantakkan Porong sejak 29 Mei 2006. Bersamaan dengan itu tak ada kejelasan waktu kapan semburan lumpur panas Lapindo memasuki fase epilog. Hanya saja, jika benar kesimpulan para ahli geologi bahwa semburan lumpur itu memakan waktu sekitar 30 tahun ke depan, maka tak ada kata yang tepat melukiskan nestapa yang menerpa kawasan Sidoarjo selain mengakui adanya kenyataan buruk di sekitar musnahnya perekonomian masyarakat. Dari sini pula timbul pertanyaan bernada filosofis, hikmah apa sesungguhnya yang dapat dipetik dari penurunan investasi di Sidoarjo? Demi memperkuat daya tahan perekonomian masyarakat di masa depan, apa yang dapat kita mengerti dari fakta dan kenyataan berkenaan dengan penurunan investasi di Sidoarjo? Mungkinkah realitas buruk sebagaimana terpampang di Sidoarjo itu hadir kembali di tempat lain di masa depan, sebagai sebuah repetisi yang sama sekali tak menghibur? Sesungguhnya, kehancuran perekonomian masyarakat Sidoarjo akibat lumpur panas Lapindo Brantas dapat ditemukan penjelasannya dari berbagai macam perspektif. Karena itu, izinkan analisis berita ini menyumbang satu perspektif untuk menyingkap hakikat kehancuran investasi di Sidoarjo. Perspektif dimaksud adalah menyibak kejatuhan investasi di Sidoarjo sebagai resultan dari kehancuran sistem kapitalistik pada ranah lokal perekonomian. Jauh sebelum petaka atau bencana lumpur panas Lapindo datang dengan membawa takdir kehancuran, Sidoarjo merupakan sub-urban dalam kedudukannya yang cukup strategis sebagai satelit perekonomian bagi Surabaya. Sementara, Surabaya sendiri merupakan ibukota Jawa Timur serta kota terbesar nomor dua di Indonesia. Itulah mengapa, Sidoarjo memiliki daya tarik sebagai salah satu tujuan investasi di Jawa Timur. Tragisnya, lumpur panas Lapindo telah mengubah segalanya. Infrastruktur yang hancur karena lumpur panas Lapindo semakin menutup kemungkinan terjadinya aliran investasi ke Sidoarjo. Bahkan, begitu spektakuler kehancuran infrastruktur itu sampai-sampai mencetuskan kerugian hingga mencapai Rp 7,6 triliun (Indo Pos, 29 Mei 2007, hlm. 8). Sementara, total kerugian versi Bappenas sejauh ini telah mencapai Rp. 27,4 triliun (editorial Koran Tempo, 28 Mei 2007). Maka, panggung perekonomian Sidoarjo pada akhirnya memang benar-benar tutup layar untuk diperhitungkan sebagai daerah tujuan investasi. Hanya saja, nestapa yang menerpa perekonomian masyarakat Sidoarjo itu tak mungkin dibaca secara telanjang sebagai akibat logis dari munculnya kekuatan tandingan terhadap kapitalisme. Perekonomian masyarakat di Sidoarjo bukanlah panggung yang mempertontokan kematian kapitalisme oleh, katakanlah, bangkitnya sosialisme. Kehancuran perekonomian masyarakat Sidoarjo justru disebabkan oleh sistem dan model kapitalistik yang inherent ke dalam pola kerja Lapindo Brantas Inc. Dengan kata lain, Sidoarjo mempertontonkan drama buruk kehancuran kapitalisme justru oleh model dan sistem kapitalisme itu sendiri yang diimplementasikan untuk tujuan lain. Secara kategoris, Lapindo Brantas Inc. bekerja sebagai agen kapitalisme pertambangan. Perlahan tapi pasti, inilah kapitalisme yang kemudian bergeser menjadi kekuatan perusak (juggernaut) terhadap kapitalisme industrial yang sebelumnya telah berjalan dan menemukan bentuknya di Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, asal mula munculnya lumpur panas di Sidoarjo terkait erat dengan pola pengusahaan pertambangan gas oleh sebuah kekuatan korporasi yang kemudian diketahui bernama Lapindo Brantas Inc. Dalam hal ini, Lapindo Brantas Inc. bergerak dengan mengadopsi sebuah prinsip perekonomian yang oleh Naomi Klein (The Nation, 2 Mei 2005) digambarkan sebagaithe rise of disaster capitalism. Logika yang bekerja dalam kapitalisme model ini adalah menekan serendah mungkin seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam hal menangkap peluang dan demi meraup keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Manakala untuk keperluan itu harus dilakukan dengan cara-cara gegabah, merusak lingkungan dan menghancurkan masyarakat, maka itulah konsekuensi yang tak terelakkan. Dengan demikian, disaster capitalism merupakan monster yang bangkit dari kancah ambisi kaum kapitalis untuk kemudian memangsa dan meluluhlantakkan kaum kapitalis yang lain. Tak cukup itu, kapitalis semacam ini menistakan masyarakat serta menghancurkan kebudayaan dan tradisi sosial pada tingkat lokal. Dengan sendirinya, Porong dalam bentangan geostrategis Sidoarjo betul-betul dinisbikan semata sebagai terra nullius atau kawasan yang dipersepsi sebagai sama sekali “tak memiliki eksistensi”. Bertitiktolak dari kenyataan ini maka muncul pertanyaan yang bercorak hipotetik: mungkinkah kapitalis memangsa kapitalis lain atau borjuasi menelan sesama borjuasi merupakan sosok kapitalisme ala Indonesia? Apakah gelombang disaster capitalism yang dipertontonkan Lapindo Brantas Inc. itu merupakan prolog yang akan diikuti oleh kemunculan disaster capitalism dalam format yang lain di masa depan? Meminjam perspektif Lester C. Thurow dalam The Future of Capitalism (New York: William Morrow & Co., Inc., 1996), ada sesuatu yang tak terperikan antara masa kini dan masa depan. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja pada hari ini, menentukan kenyataan masa depan. Ini berarti, ada semacam bola salju persoalan yang jika menggelinding bakal membesar dengan intensitas yang kian tinggi. Disaster capitalism lalu menjadi semacam petaka yang melahirkan karma di masa depan jika tak diamputasi dengan segera saat ini juga. Pemerintah merupakan regulator yang memiliki otoritas penuh memotong segenap kemungkinan timbulnya karma disaster capitalism. Sayangnya rezim kekuasaan pengendali pemerintahan kini sangat lembek berhadapan dengan kaum kapitalis pemilik Lapindo Brantas Inc. Rezim kekuasaan kini seakan buta dan tuli, bahwa setahun lumpur panas Lapindo muncrat telah menistakan kehidupan anak-anak bangsa secara amat telanjang, di sana, di Porong sana, di sana ….. di sana …. Rezim kekuasaan loyo politik semacam inilah yang mengondisikan munculnya Lapindo-lapindo yang lain di tempat lain. by: citra yudha erlanggaSetahun Lumpur Panas Lapindo porong (Jawa Timur)
Selamat Datang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Silahkan Cari disini
My Zodiak

MayQ
Lambang Negara Indonesia
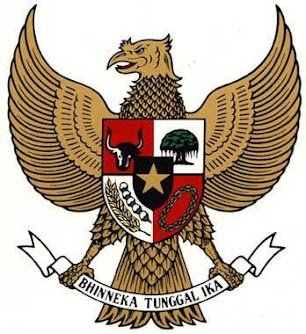
Garuda Pancasila
Lambang Pramuka Garuda

Penegak Laksana
Boy Scout

Logo Pramuka Putra
Lambang POLRI

Aku Suka Itu
Saka Bhayangkara

Anggota Saka Bhayangkara
Tunas Bangsa
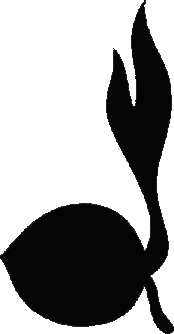
Lambang Gerakan Pramuka
Sekarang jam Berapa yaCh ???
Tanggal Berapa Yach ???
Thank's for invite
Labels-
Berikan Komentar.Ok?!
Daftar My Friend
- Abdul hafidz.A
- Achmad irvansyah
- Alda Blanov
- Aldhi Mandiri
- Amrizal Ardi S
- Danu Raskiantoro
- Dewi Lusitasari
- Dwi Ary A
- Eka Firmansyah
- Farah Febria N
- Febri Ibnu D
- Febriyan Haris A
- Firman Saputra A
- Gandi Rachmad
- Iwan Hadi W
- Kurniati Setya N
- M.Alfiyan
- M.Denny
- M.Rozikin
- M.Zakaria
- Naning Widiarti
- Niken Widyaningtyas
- Prawira Aditama P
- Purwoadi S
- Rachmad Ade
- Rachmad Akhlakul K
- Rahditya Surya P
- Ranee Elisa I
- Renny Putri W
- Satria Imam M
- Tanzil Alfian H
- Wulan Novitasari
- Yeni Fay
Translator bahasa
by : BTF













1 komentar:
Mas,
Ijin muat tulisan di web http://korbanlapindo.net
Klo boleh, kontak sy di winarko.winarko@gmail.com
Suwun
Win
Posting Komentar